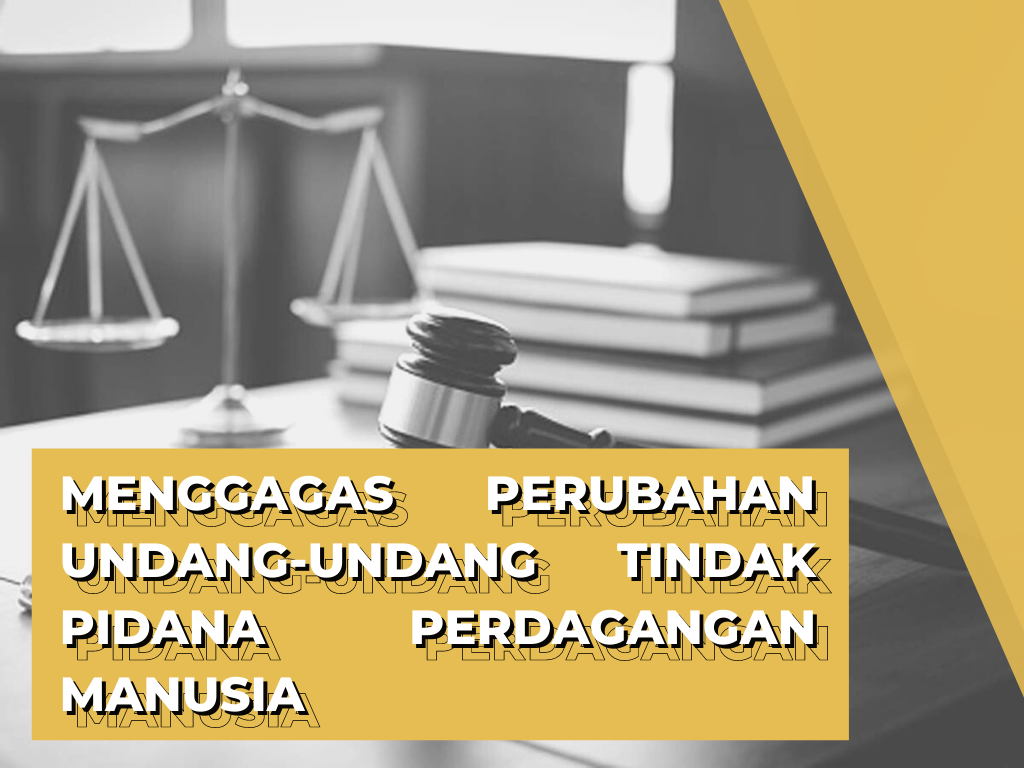Oleh : Trian Marfiansyah
(Internship Advokat Konstitusi)
Majunya peradaban identik dengan kemajuan pola pikir manusia yang mengantarkan kepada kemutakhiran teknologi dan regulasi. Dengan ini, masyarakat diharapkan untuk mempunyai kehidupan yang lebih sejahtera, modern, dan adanya rasa aman. Namun senyatanya, budaya lampau seperti perbudakan masih marak terjadi dan menjadi permasalahan dunia. Salah satu bentuk perbudakan tersebut adalah perdagangan manusia. Seringkali, korban seperti anak-anak, laki-laki, dan perempuan dewasa dieksploitasi untuk melakukan berbagai ‘pekerjaan seks’, seperti prostitusi, bahkan kawin paksa. Hal tersebut menjadi cerminan tersendiri bagi negara dalam menjamin perlindungan korban terhadap perdagangan manusia.
Disamping berpotensi mendapatkan penyakit menular, hal tersebut dapat memperburuk psikologis korban kedepannya. Dalam perspektif manapun, kejahatan ini sangat menyalahi Hak Asasi Manusia (HAM) setiap individu. Laporan Tahunan tentang perdagangan manusia dari Departemen Luar Negeri Amerika mencatat sedikitnya 25 juta orang menjadi korban kejahatan ini. Sementara di Indonesia, bila mengacu data Kementerian Sosial dari 2016 hingga Juni 2019, terdapat 4.906 korban tindak pidana perdagangan orang. Adapun data lain dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyebutkan terdapat 155 kasus tindak pidana perdagangan orang dengan 195 korban perempuan dan anak selama Januari 2019 hingga Juni 2020.
Tindak pidana perdagangan manusia diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Pasal 2 ayat (1) UU tersebut menjelaskan bahwa cakupan tindak pidana perdagangan manusia terdiri dari perekrutan, penampungan, memindahkan, mengirim, ataupun menerima seseorang dengan melakukan ancaman kekerasan bahkan melakukan penyekapan, menculik, menipu, memalsukan, menyalahgunakan posisi kekuasaan, menjerat seseorang dengan utang lalu memanfaatkannya dengan bertujuan untuk mengeksploitasinya. Pasal yang sama juga menerangkan bahwa ancaman hukuman terkait berupa pidana penjara antara tiga hingga 15 tahun penjara, sedangkan dendanya maksimal Rp. 600.000.000,00. Tindak pidana tersebut juga harus disertai berbagai unsur untuk dipenuhi, yaitu pelaku, tindakan, modus, dan tujuan.
Umumnya kejahatan ini didukung oleh faktor kesemrawutan ekonomi, konflik pribadi, bahkan bencana alam sehingga memaksa warga untuk melakukan pekerjaan imigrasi guna bertahan hidup. Tidak heran jika klasifikasi korban yang terimbas umumnya berupa imigran yang diangkut, penculikan oleh mucikari, perekrutan gelap, bahkan pembelian paksa oleh para pelaku yang cukup menggambarkan faktor-faktor tersebut. Sayangnya, masyarakat maupun penegak hukum memandang kejahatan ini terfokus kepada wanita sebagai budak seksual, padahal anak-anak dan laki-laki juga kerap dikorbankan.
Lanjutnya, perihal penegakkan UU PTPPO seringkali harus melibatkan saksi untuk mekanisme pembuktian. Saksi yang dimaksud meliputi agen dari perekrutan tenaga kerja, calo dari pelaku, pengelola ataupun pemilik dari rumah bordil, oknum pemerintah yang terlibat memberikan akses imigrasi, dan majikan dari para korban. Dalam Pasal 41 ayat (1) UU PTPPO disebutkan apabila dalam tahap persidangan terdakwa tidak hadir maka persidangan tetap dilanjutkan dan diputuskan tanpa kehadiran terdakwa. Jika terbukti bersalah, Pasal 7 ayat 1 menjelaskan bahwa pertambahan ancaman hukuman pidana bagi pelaku memberikan penganiayaan kepada korban mendapatkan ancaman pidana ditambah sepertiga dengan maksimal 20 tahun dan minimal empat tahun penjara dengan denda paling banyak yaitu Rp. 800.000.000,00.
Dalam perspektif hukum internasional, suatu perjanjian atau treaty contract menjadi salah satu sumber hukum untuk memberikan legitimasi negara-negara dunia menanggulangi kejahatan internasional. Konvensi Protokol Palermo menjadi salah satu perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Indonesia terkait perdagangan manusia. Negara anggota dalam konvensi tersebut haruslah menerapkan langkah-langkah legislatif dan bila dirasa perlu dapat menindak, menghukum, maupun melakukan pencegahan terkait dengan perdagangan manusia, khususnya anak-anak dan perempuan.
Sejak tanggal 19 april 2007, sebelum diratifikasi, UU PTPPO ternyata telah diundangkan terlebih dahulu. Sehingga, Indonesia mengajukan diri untuk membantu dan mencegah kejahatan tersebut dengan cara apapun berdasarkan Egality Rights dan Pacta Sund Servanda sesama anggota. Komparasi Protokol Palermo dengan UU PTPPO menghasilkan segelintir perbedaan. Pada UU PTPPO, dijelaskan tidak adanya kata perbudakan dan tidak menyebutkan frasa eksploitasi seksual melainkan frasa memegang kendali sehingga memberikan artian yang berbeda bagi setiap orang yang membacanya. Lalu, rehabilitasi bagi korban kejahatan perdagangan manusia tidak diatur dalam Protokol Palermo, namun tertera di UU PTPPO. Hal demikian bertujuan untuk membebaskan negara masing-masing untuk menentukan ketentuan peraturan yang cocok menyesuaikan kondisi negaranya.
Protokol Palermo mengatur mengenai definisi dari dari perdagangan anak sedangkan UU PTPPO tidak. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan spesifik mengenai hak asasi anak. UU tersebut tidak menjadikan kejahatan perdagangan anak sebagai tindakan kriminal dengan unsur memperhatikan metode pelaku dalam mengeksploitasi anak tersebut. Dengan kata lain, cara spesifik eksploitasi anak kurang diatur dalam UU tersebut meskipun telah diamanatkan dalam Protokol Palermo.
Selain itu, tidak adanya pengertian mengenai eksploitasi seksual yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (8) UU PTPPO, dapat menjustifikasi pembaca bahwa pelacur sebagai bentuk kriminal padahal belum tentu itu merupakan tindak kejahatan perdagangan manusia. Orang-orang tersebut bisa saja memilih sebagai pekerja seks untuk menyambung hidup. Sehingga, hal ini secara tidak langsung menyudutkan perempuan.
Melibatkan regulasi lain seperti UU Keimigrasian, UU Perlindungan Anak, KUHP, UU Ketenagakerjaan, UU Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri memberikan kesulitan bagi para penegak hukum karena harus bersifat koordinatif dalam pemberantasannya. Tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 bahwa terdapat gugus tugas dalam penangannya namun dinilai masih kurang efektif karena kesulitan mendapatkan legitimasi perintah dan praktek lapangan penempatan TKI yang ceroboh tanpa disertai perlindungan gugus tersebut. Padahal, negara selaku pelayan publik sudah seharusnya memprioritaskan revisi regulasi tersebut untuk memberantas dan mencegah kejahatan transnasional tersebut.
Lalu, minimnya pengaturan mekanisme pelaporan yang masih rancu mengakibatkan korban atau saksi menjadi takut melapor kepada pihak berwajib. Dalam hal ini dapat menghilangkan rasa aman dari publik dan memicu distrust masyarakat terhadap pemerintah. Maka, idealnya harus dijelaskannya secara spesifik terkait mekanisme pelaporan dan perlindungan apa saja yang korban peroleh baik secara nasional maupun internasional.
Adapun hak-hak yang sudah dipaparkan dalam UU PTPPO terdapat dalam Pasal 43 hingga 45 meliputi hak memakai segala upaya hukum, hak memperoleh kompensasi, hak memperoleh penasehat hukum, hak memperoleh perlindungan hukum, hak rehabilitasi, dan hak memperoleh kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya. Lalu, dalam Pasal 48 dijelaskan bahwa korban tentu berhak memperoleh restitusi pada saat ia melaporkan kejadiannya. Sehingga secara normatif, dalam melakukan upaya hukum setidaknya sang korban memiliki perlindungan dalam upaya hukum baik di dalam maupun luar pengadilan.
Penulis berkesimpulan bahwa UU PTPPO sudah dirancang dengan cukup baik namun masih memerlukan revisi substansi dan juga peraturan pelaksana demi terpenuhinya perlindungan korban yang dituju. Sejatinya, perdagangan manusia dengan motif apapun tidak dapat dihalalkan. Sehingga, hanya gerakan kolektif beserta kebijakan kemanusiaan selaku solusi dalam mencegah kejahatan HAM serupa kedepannya. ()